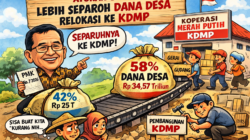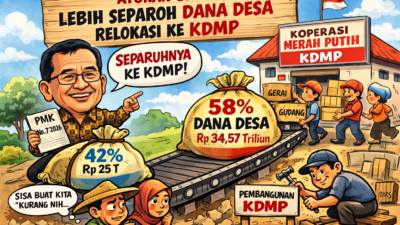Oleh: Novita Sari Yahya
Dari Nilai A ke Jurusan Biologi
Ilmu pengetahuan yang belum saya coba untuk dalami serius adalah matematika dan fisika. Ironisnya, waktu SD di Malaysia saya bisa dapat grade A di semua pelajaran. Waktu SMP, nilai Ebtanas matematika saya 9 lebih. Tapi ketika masuk SMA, barulah saya sadar: ternyata otak saya tidak seindah rapor. Matematika mulai menampakkan taringnya, fisika jadi monster yang lebih menakutkan dari guru killer, sementara biologi dan bahasa seperti pacar yang manis—selalu bikin nyaman. Tidak heran akhirnya saya masuk jurusan biologi, bukan fisika. Pilihan aman.
STEM dan Warisan Soekarno
Sekarang istilah kerennya adalah STEM—Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Katanya itu fondasi dunia modern. Dulu, pada zaman Soekarno, ribuan mahasiswa Indonesia dikirim ke Rusia, Tiongkok, Eropa Timur, bahkan Korea Utara. Tujuannya jelas: pulang, lalu bangun Indonesia.
Soekarno adalah figur revolusioner yang penuh semangat. Dengan pidatonya, ia bisa membuat rakyat bergetar, bahkan lantang menyerukan “Ganyang Malaysia!” yang sampai sekarang masih jadi kutipan legendaris. Namun, di balik semangat membakar itu, ada paradoks: beberapa kawan seperjuangan justru dimasukkan ke penjara karena beda haluan. Tokoh seperti Mohammad Natsir, Sutan Sjahrir, hingga Buya Hamka merasakan hal tersebut. Kritik Bung Hatta tentang “persatean” Nasakom pun tenggelam di tengah retorika Bung Karno yang selalu dramatis dan memikat.
Mahasiswa Indonesia di Blok Timur
Namun, kalau tragedi 1965 tidak terjadi, mungkin jalan sejarah lain. Ribuan mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri bisa pulang dan membangun negeri. Bayangkan jika mereka membawa ilmu dari Rusia, Eropa Timur, atau Tiongkok—ilmu yang bahkan tak ada di Cambridge atau Oxford.
Korea Utara misalnya, walau miskin, unggul dalam nuklir dan teknologi kesehatan. Mahasiswa Indonesia di era itu ada yang belajar teknik perkeretaapian Soviet, rekayasa nuklir, hingga kedokteran tropis berbasis sistem komunal Tiongkok. Ilmu yang kala itu mustahil ditemukan di universitas Barat karena dianggap “tidak sesuai selera kapitalisme.” Tapi, semua itu berakhir tragis: mereka dibantai, dipenjara, atau tak bisa pulang. Sejarah Indonesia kehilangan generasi emas ilmu pengetahuan.
1965: Ilmu yang Hilang dan Generasi yang Terkorbankan
Tragedi politik 1965 bukan hanya soal perebutan kuasa, tapi juga pemangkasan brutal terhadap potensi akademik bangsa. Ribuan intelektual yang dianggap “kiri” lenyap begitu saja. Banyak mahasiswa Indonesia di luar negeri menjadi eksil, tak bisa kembali karena khawatir ditangkap. Mereka hidup di pengasingan, dari Praha, Moskow, hingga Beijing. Pertanyaannya: seandainya mereka pulang dan berkarya, apakah Indonesia hari ini bisa menyalip Tiongkok? Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban.
Orde Baru dan Lahirnya Ilmu “Komisiologi”
Masuk era Orde Baru, Soeharto membangun sistem pembangunan dengan arahan Amerika Serikat dan sekutunya: IMF, Bank Dunia, dan lembaga donor lainnya. Mahasiswa Indonesia mulai dikirim belajar ke AS, Inggris, Australia, dan Belanda. Apa hasilnya? Banyak yang pulang membawa ilmu, tapi pemerintah tidak punya ruang menampungnya. Jurusan macam astrofisika, bioteknologi, atau teknik nuklir? Tidak ada kementerian yang peduli.
Akhirnya lulusan-lulusan cemerlang itu justru terserap di perusahaan asing atau sekadar jadi konsultan proyek. Sementara yang meroket di dalam negeri adalah ilmu “komisiologi”—seni mendapatkan komisi dari setiap proyek SDA. Inilah masa ketika jargon paling populer bukan STEM, melainkan “asal bapak senang” dan “bapak/ibu komisi.”
Sarjana Luar Negeri: Dari Beasiswa ke Buzzer
Apa yang dilakukan para sarjana jebolan kampus top dunia? Banyak yang akhirnya bekerja di perusahaan dengan saham mayoritas asing, atau sibuk rebutan jabatan komisaris BUMN. Bukan karena prestasi, tapi karena koneksi.
Lebih parah lagi, banyak dari mereka berubah jadi gelandangan politik. Kerjaannya ribut di media sosial, bikin meme, jadi buzzer. Kalau bos yang didukung menang pilpres, langsung naik pangkat jadi staf ahli atau komisaris. Ironisnya, mereka lebih sering memproduksi hoaks dan gosip ala emak-emak komplek daripada jurnal riset. Inilah tragedi pendidikan tinggi Indonesia: dari beasiswa rakyat, hasilnya malah jadi konten kreator politik.
Matematika dan Fisika: Dari Saya ke Generasi Berikutnya
Jadi mari kita kembali ngopi pagi, membicarakan kelemahan saya di bidang matematika dan fisika. Untungnya, ada harapan: putra saya yang paling tua justru cemerlang di bidang fisika dan matematika. Ia berhasil lulus teknik sipil, meski dari perguruan tinggi swasta. Hasil tes IQ-nya juga menunjukkan kemampuan kuat di bidang STEM. Ketika saya dorong melanjutkan kuliah S2, jawabannya sederhana: “uang lebih penting daripada ijazah.”
Itulah salah satu penyebab generasi muda Indonesia tidak berlomba-lomba di bidang pengetahuan. Mereka lebih suka mencari jalan pintas pragmatis. Meski begitu, saya tetap optimis: suatu saat akan kembali era di masa awal kemerdekaan, ketika manusia Indonesia lebih haus ilmu daripada haus jabatan.
Harapan Baru dari Generasi Z
Beberapa waktu lalu, ada berita menggembirakan: Generasi Z mulai bangkit dengan literasi, membeli buku, dan berkumpul dalam komunitas membaca. Sebuah tanda bahwa gairah ilmu pengetahuan belum padam sepenuhnya.
Harapan saya lainnya: suatu hari lahir yayasan filantropi desa yang fokus pada riset dan pengembangan teknologi sederhana. Dari desa bisa lahir pemikir besar, ahli matematika, bahkan fisikawan yang menciptakan mesin cerdas lebih pintar dari Grok atau ChatGPT. Desa yang modern tapi tetap tradisional, dengan masyarakat yang gemar membaca, menulis, dan berdiskusi.
Itulah imajinasi saya tentang Indonesia: negara yang bukan hanya pandai bikin meme politik, tapi juga menghasilkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.