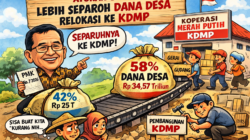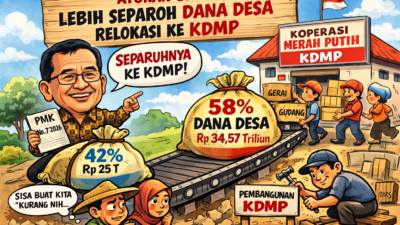Di era digital saat ini, salah satu bentuk hiburan sekaligus cermin sosial yang paling sering kita temui di media sosial adalah meme—terutama yang menampilkan wajah pejabat negara. Jika dilakukan survei global, hampir pasti Indonesia termasuk negara dengan jumlah meme terbanyak yang menyorot perilaku pejabat publik.
Oleh: Novita Sari Yahya
Fenomena ini tidak hanya menunjukkan tingginya kreativitas masyarakat, tetapi juga menggambarkan keresahan dan kritik sosial terhadap penguasa.
Sastrawan Mochtar Lubis pernah menyebut bangsa Indonesia sebagai bangsa yang artistik. Kreativitas ini tampak jelas dalam cara masyarakat menanggapi situasi politik dan fenomena sosial melalui humor, satire, dan meme yang cepat viral. Namun, jika dicermati lebih dalam, meme juga mencerminkan mentalitas bangsa yang tumbuh dari sejarah panjang penjajahan dan warisan post-kolonial.
Dalam tulisannya di Kompas (4 Desember 2010) berjudul Inlander Dinilai, Rosihan Anwar mengutip pandangan wartawan Belanda Willem Walraven tentang mentalitas “inlander” — sebutan kolonial untuk penduduk pribumi. Dalam suratnya kepada pengarang Rob Nieuwenhuys pada 15 Maret 1941, Walraven menulis bahwa orang Indonesia sangat gemar berpolitik, bahkan dalam kehidupan sehari-hari: “Hidup pun berpolitik, mati pun berpolitik.” Konflik lokal kerap muncul dari hal-hal sepele, menandakan kohesi sosial yang rapuh.
Rosihan juga mengutip pengamatan seorang rohaniwan Belanda yang telah 30 tahun tinggal di Indonesia — sebagaimana tertulis dalam buku Wischer Hulst, Becakrijders, Hoeren, Generaals en andere Politici (1980) — yang menilai bahwa bangsa Indonesia adalah “bangsa politisi,” karena mereka dilahirkan dengan naluri politik dan mati dengan cara itu pula.
Pertanyaannya: apakah mentalitas kolonial ini masih relevan setelah lebih dari delapan dekade kemerdekaan? Fenomena ini dapat dijelaskan melalui istilah amnesia post-kolonial, yaitu kondisi ketika mentalitas lama yang seharusnya terkikis justru masih melekat dalam perilaku sosial dan politik bangsa.
Salah satu contohnya terlihat dari respon masyarakat terhadap meme pejabat. Banyak meme bersifat satire, bahkan kasar, tetapi tidak selalu menimbulkan perubahan perilaku. Sementara keluarga pejabat mungkin merasa malu, sistem sosial dan mental kolonial—seperti hipokrisi, penghindaran tanggung jawab, dan materialisme—membuat banyak orang merasa aman selama kehidupan materi mereka tetap nyaman.
Kasus nyata dapat dilihat pada kerusuhan 30 Agustus 2025 yang berujung pada penjarahan rumah anggota DPR di Jakarta (Tempo, 2025). Meski ada simpati publik terhadap aksi tersebut, pada akhirnya kenyamanan materi tetap menjadi prioritas. Ribuan meme dan ejekan yang beredar tidak membawa efek jera bagi penguasa.
Jika dibandingkan dengan kultur politik di negara maju seperti Jepang, perbedaannya sangat mencolok. Pejabat yang terlibat korupsi di sana biasanya langsung mengaku salah, meminta maaf, bahkan mundur dari jabatan demi menjaga kehormatan publik. Sementara di Indonesia, koruptor masih bisa tersenyum di depan kamera, bahkan mengenakan rompi tahanan seolah itu sekadar formalitas. Air mata mereka lebih sering muncul karena ingin dikasihani, bukan karena menyesal.
Mengapa banyak orang Indonesia lebih takut miskin daripada takut penjara? Materi masih dianggap sebagai ukuran utama kehormatan dan keberhasilan. Padahal, hukuman efektif bukan hanya penjara, tetapi juga perampasan total aset hasil korupsi. Tanpa materi, gaya hidup glamor dan simbol kekuasaan akan hilang—dan kekuatan sosial mereka ikut melemah.
Sayangnya, hukum di Indonesia belum menegakkan perampasan aset secara menyeluruh. Menurut laporan Transparency International (2024), dari 5.000 kasus korupsi besar, hanya sekitar 27% aset berhasil dikembalikan ke negara. Data ini memperkuat kesan bahwa perubahan mental dan moral pejabat masih jauh dari harapan.
Meme memang alat kontrol sosial yang kuat, tetapi tidak cukup untuk mengubah sistem yang korup dan tidak transparan. Dibutuhkan reformasi hukum yang tegas serta budaya politik yang berintegritas, agar pejabat publik benar-benar takut melanggar hukum dan bertanggung jawab atas perbuatannya.
Kita bisa belajar dari Jepang atau negara-negara Skandinavia, di mana pejabat korup menghadapi hukuman berat, wajib mengembalikan aset, dan menerima tekanan sosial besar. Budaya malu dan tanggung jawab membuat mereka memilih mundur demi menjaga kehormatan pribadi dan institusi.
Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan penegakan hukum yang konsisten, agar tidak terus terjebak dalam mental “inlander” yang mengalami amnesia post-kolonial—mental yang takut kehilangan harta tetapi enggan bertanggung jawab.
Meme bukan sekadar hiburan, tetapi tanda tanya besar tentang sejauh mana bangsa ini mampu mengikis mental feodal dan membangun budaya demokrasi yang bermartabat. Revolusi mental tidak akan berhasil tanpa penegakan hukum yang adil dan masyarakat yang berani menuntut pertanggungjawaban.
Jika pejabat gagal menjadikan meme sebagai bahan introspeksi, masyarakat tidak boleh berhenti menggunakan satire sebagai alat kontrol sosial. Namun lebih dari itu, suara rakyat harus difasilitasi dalam sistem yang transparan dan berkeadilan, agar mental feodalisme benar-benar tergantikan oleh budaya demokrasi yang jujur dan beradab.(*)
Referensi
-
Anwar, Rosihan. 2010. “Inlander Dinilai.” Kompas, 4 Desember.
-
Hulst, Wischer. 1980. Becakrijders, Hoeren, Generaals en andere Politici.
-
Tempo. 2025. “Kronologi Demo Memprotes DPR hingga Meluas Berubah Penjarahan.” 31 Agustus.
-
Transparency International. 2024. Corruption Perceptions Index 2024.
✍️ Novita Sari Yahya
Penulis dan Peneliti
Instagram: @novita.kebangsaa
CP Pembelian Buku: 0895-2001-8812