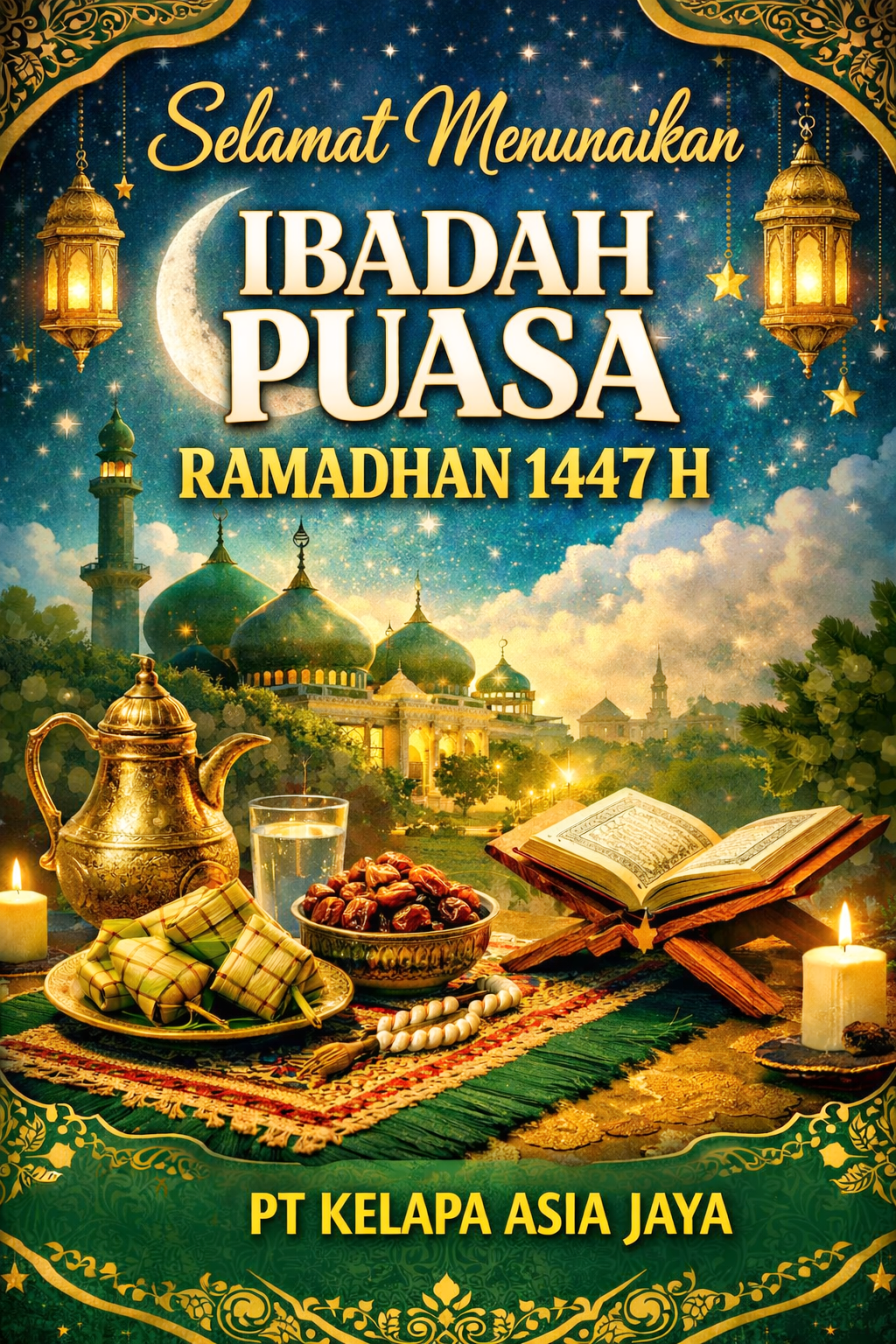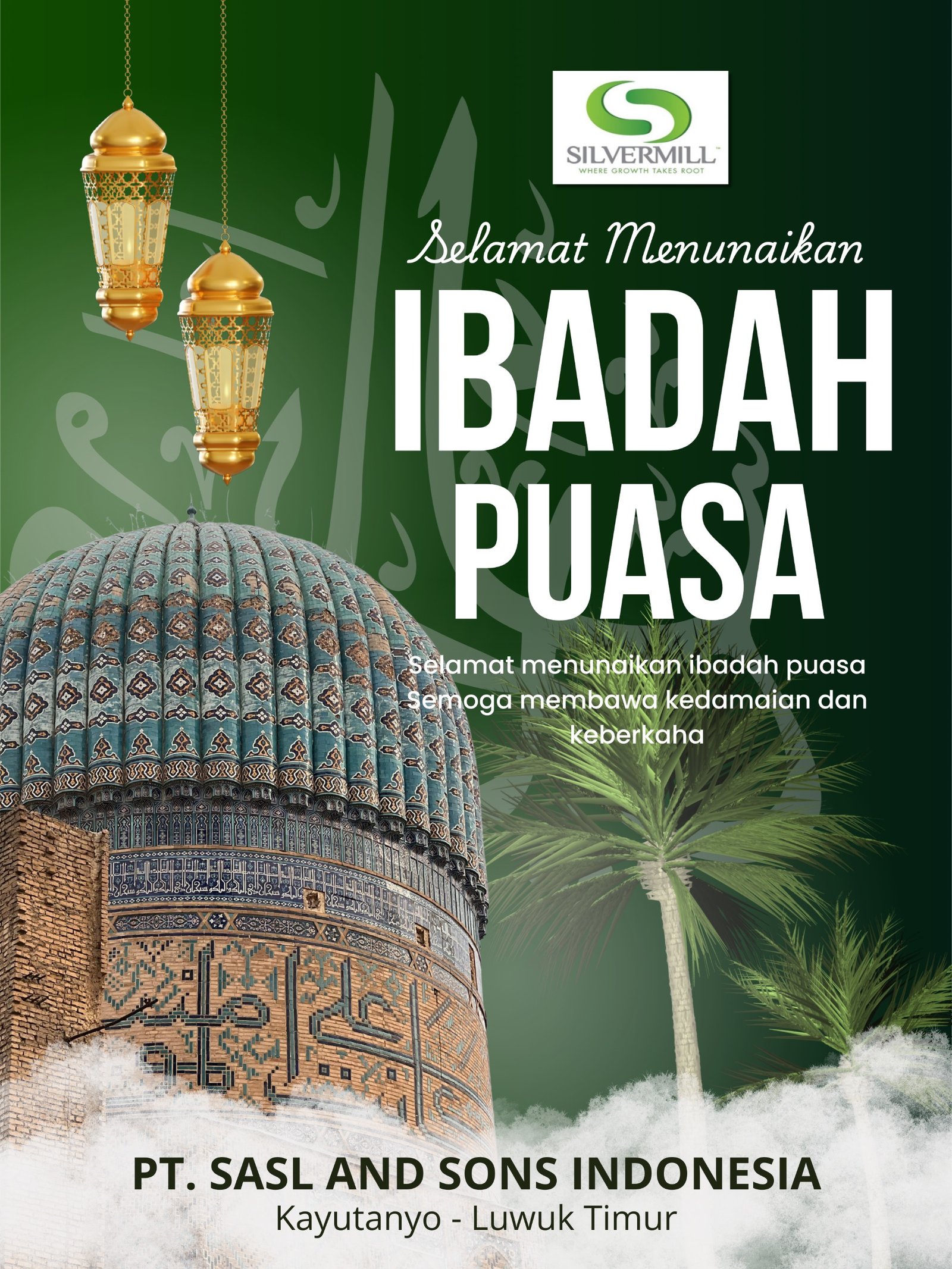Oleh: Supriadi Lawani
Negara ini kerap membanggakan diri sebagai negara hukum. Konstitusi bahkan menegaskannya dengan percaya diri: Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.
Namun pernyataan itu runtuh seketika ketika seorang bupati bisa kalah di semua tingkat pengadilan, tetapi tetap menang dalam praktik kekuasaan.
Kasus di Kabupaten Banggai adalah contoh telanjang. Bupati Banggai kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Ia banding ke PTTUN Makassar—kalah lagi. Ia kasasi ke Mahkamah Agung—kalah lagi. Putusan sudah inkracht, final, mengikat, dan seharusnya dilaksanakan.
Namun hingga kini, jabatan Marsidin Ribangka tidak dikembalikan. Putusan pengadilan dibiarkan menggantung, tak bertaji, tak bermakna.
Di titik inilah kita patut bertanya: siapa sebenarnya yang kalah? Apakah bupati? Atau justru negara itu sendiri?
Dalam sistem hukum administrasi, putusan PTUN bukan sekadar koreksi administratif. Ia adalah perintah negara kepada pejabat publik untuk memulihkan hak warga dan menata ulang tindakan pemerintahan yang melanggar hukum.
Ketika perintah itu diabaikan, yang dilanggar bukan hanya putusan hakim, tetapi prinsip dasar negara hukum.
Ironisnya, negara tampak tidak berdaya menghadapi pembangkangan pejabatnya sendiri. Undang-undang memang menyediakan instrumen: uang paksa (dwangsom), sanksi administratif, hingga pelaporan kepada Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Namun semua itu sering berhenti sebagai norma di atas kertas.
Tidak dijalankan. Tidak dipaksakan. Tidak ditindaklanjuti dengan keberanian politik.
Akibatnya fatal. Pengadilan menang secara hukum, tetapi kalah secara nyata. Bupati kalah di atas kertas, tetapi berkuasa penuh di lapangan. Putusan hakim berubah menjadi dokumen arsip, bukan alat keadilan. Dalam situasi seperti ini, rakyat belajar satu pelajaran berbahaya: taat hukum itu opsional bagi penguasa.
Lebih jauh, ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan adalah bentuk penghinaan terhadap negara itu sendiri. Ia menegaskan bahwa kekuasaan eksekutif lokal dapat berdiri di atas hukum, tanpa rasa takut, tanpa sanksi berarti. Jika bupati hari ini bisa mengabaikan Mahkamah Agung, lalu apa bedanya kita dengan negara yang diperintah oleh kehendak personal?
Kasus Banggai bukan soal Marsidin Ribangka semata. Ini soal efektivitas hukum, soal wibawa pengadilan, dan soal keberanian negara menertibkan pejabatnya sendiri. Jika negara kalah di hadapan bupati, maka yang runtuh bukan hanya satu putusan, melainkan kepercayaan publik terhadap keadilan.
Negara hukum tidak diukur dari banyaknya peraturan atau megahnya gedung pengadilan, tetapi dari satu hal sederhana: apakah putusan hakim dijalankan atau tidak. Jika jawabannya tidak, maka klaim negara hukum hanyalah slogan kosong.
Dalam perkara ini, yang sesungguhnya kalah bukan bupati. Yang kalah adalah negara. Dan ketika negara kalah, rakyatlah yang paling duluan membayar ongkosnya.
Luwuk 15/1/2026
Penulis adalah petani pisang yang kadang jadi advokat